Oleh: Azis Subekti, Anggota DPR RI Komisi II, Dapil Jawa Tengah VI
Ada lanskap yang tak pernah meminta apa-apa selain dijaga. Danau Menjer adalah salah satunya. Di lingkar pegunungan Dieng, danau ini selama puluhan tahun bekerja sunyi: menahan air hujan, menenangkan aliran, dan memberi kehidupan bagi warga di sekitarnya. Namun hari-hari ini, ketenangan itu retak—bukan oleh alam, melainkan oleh keputusan manusia.
Gambar-gambar yang viral dari Desa Maron, Garung, Wonosobo, Jawa Tengah bukan sekadar soal pemandangan yang berubah. Ia adalah penanda arah. Bangunan-bangunan komersial tumbuh di kawasan tangkapan air—wilayah yang semestinya dilindungi—menggerus sempadan, memotong infiltrasi, dan mempercepat sedimentasi. Air yang dahulu jernih kini mudah keruh selepas hujan; lereng yang dulu menyerap kini mengalirkan lumpur.
Kecurigaan warga tentang pembiaran tak lahir dari prasangka, melainkan dari pengalaman. Ketika garis larangan menjadi ruang tawar, ketika izin tak jelas namun bangunan tetap berdiri, kepercayaan publik pun terkikis. Padahal tata ruang adalah janji antargenerasi: ia memastikan pembangunan hari ini tidak menagih bencana esok hari.
Kita perlu jujur pada diri sendiri. Pariwisata yang dikejar cepat tanpa prasyarat ekologis hanya memindahkan biaya ke masa depan. Danau vulkanik seperti Menjer memiliki daya dukung terbatas. Sekali fungsi hidrologisnya rusak, ongkos pemulihan jauh melampaui pemasukan jangka pendek. Yang terancam bukan hanya ekosistem, tetapi keselamatan warga—banjir bandang di hilir, longsor lereng, dan penurunan kualitas air yang kembali ke dapur keluarga.

Karena itu, seruan warga agar pemerintah daerah segera melakukan audit lingkungan patut disambut sebagai ajakan menata ulang arah, bukan ditafsirkan sebagai penolakan terhadap usaha. Audit yang menyeluruh—kepatuhan sempadan danau, status perizinan, beban bangunan terhadap lereng, hingga proyeksi sedimentasi—perlu dilakukan dan diumumkan secara terbuka. Penertiban bangunan liar yang melanggar tata ruang adalah langkah awal untuk memulihkan keadilan ekologis.
Namun penertiban saja tak cukup. Menjer membutuhkan kebijakan yang menyeimbangkan keberanian dan empati: moratorium pembangunan baru di zona rawan; pemulihan vegetasi penutup dengan spesies lokal; model wisata berjejak rendah yang mengutamakan fasilitas non-permanen; serta insentif bagi warga yang menjaga tutupan lahan. Pemantauan berkala kualitas air dan erosi harus menjadi kebiasaan, agar keputusan berdiri di atas data, bukan sekadar reaksi atas viralitas.
Pada akhirnya, ini bukan perkara danau semata. Ini perkara nurani. Alam tidak bersuara, tetapi ia memberi tanda. Menjer sedang berbicara melalui air yang keruh dan lereng yang rapuh. Mari kita menjawabnya dengan kebijakan yang tegas dan hati yang jernih—agar pembangunan tetap berjalan, namun kehidupan tetap berlanjut.







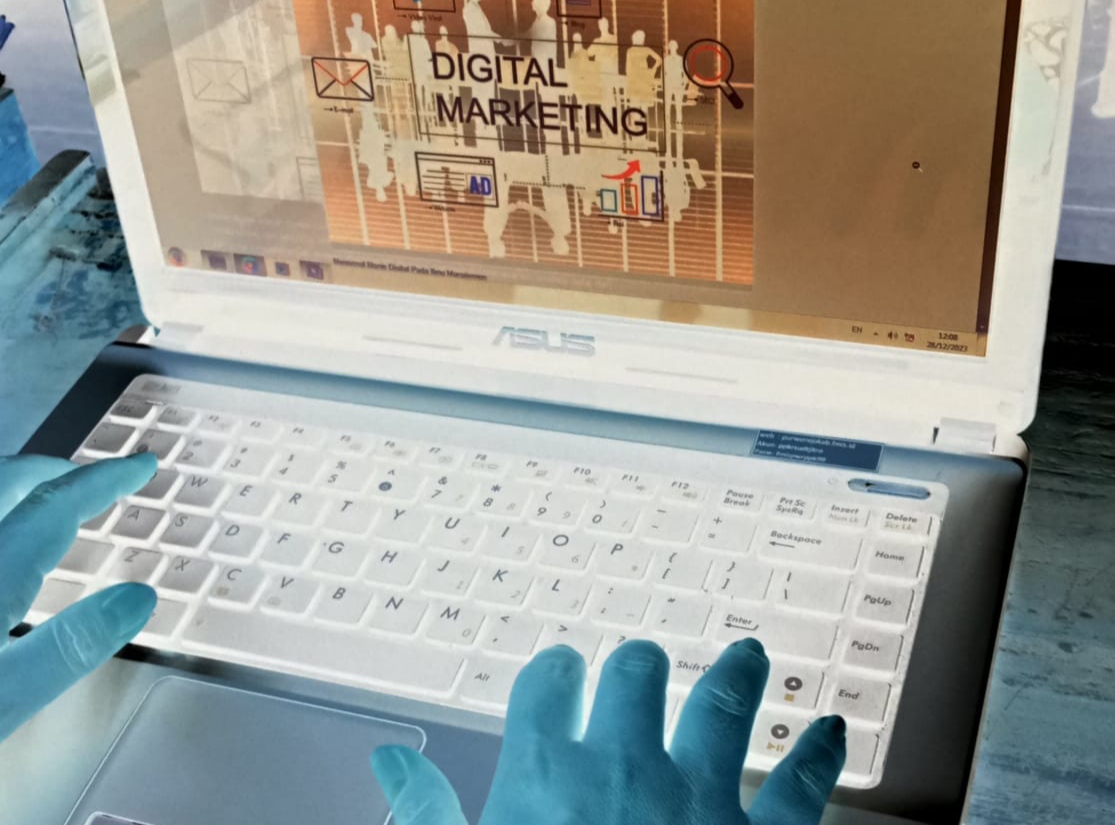










































Comment